Di Rumahmu Sendiri: Diam Atau Terlupakan!

|
| Ilustrasi. (Foto: Poetry Foundation/David Cooper). |
Tibull & Joys
*Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah
Kuala
Hutan jadi ladang, sungai jadi limbah. Kala sawit bertumbuh dan tercabutnya akar sejarah. Lantas apa yang bisa kita lakukan?
koranaceh.net
‒ Kian masifnya ruang gerak perusahaan kepala sawit di Aceh Singkil telah
memberi beragam masalah. Meski dipercaya punya kontribusi positif terhadap
ekonomi, belum tentu hal kontribusi yang sama juga mereka berikan kepada
alam dan lingkungan sekitarnya.
Ambil contoh peristiwa yang melibatkan PT Socfindo Laebutar tahun 2018 silam. Waktu itu,
sungai di Aceh Singkil tercemar akibat jebolnya kolam limbah hasil
pengolahan minyak mentah kelapa sawit mereka. Teranyar, PT Ensem Lestari diduga menjadi pelakunya. Sungai Cinendang yang berada tak jauh dari lokasi
perusahaan itu beroperasi jadi korbannya.
Ada juga pembukaan lahan perkebunan sawit ilegal yang perlahan menggerus
kawasan suaka margasatwa Rawa Singkil. Padahal, kawasan itu berstatus
wilayah hutan gambut serta menjadi rumah bagi satwa-satwa endemik.
Baca Juga :
Deforestasi Aceh Meningkat 19 Persen pada 2024, 10.610 Hektare Tutupan
Hutan Hilang
Tak hanya itu, dari aspek pelaksanaan kepatuhan terhadap aturan
perundang-undangan, terdapat sembilan perusahaan yang belum melaksanakan
kewajiban plasma. Sembilan perusahaan itu adalah PT Perkebunan Lembah Bhakti
1; PT Perkebunan Lembah Bhakti 2; PT Runding Putra Persada; PT Singkil
Sejahtera Makmur; PT Nafasindo, PT Socfindo; PT Delima Makmur; PT Ensem
Lestari; dan PT Riztia Karya Mandiri. Ditambah lagi dengan soal perizinan
Hak Guna Usaha (HGU), ada beberapa perusahaan yang tetap beroperasi sampai
saat ini meski izinnya sudah kedaluwarsa.
Berkaca dari kejadian-kejadian di atas, maka wajar kalau masyarakat Aceh
Singkil berharap persoalan ini segera tuntas. Namun yang terjadi justru
sebaliknya. Pemerintah seolah abai dan tidak berpihak pada kepentingan
rakyat. Suara-suara miring yang tertuju kepada para pemangku kebijakan
lantas jadi semakin nyaring. Spekulasi-spekulasi yang muncul pun kian liar.
Ruang-ruang publik seakan penuh terisi dengan ketidakpercayaan.
Menilik jauh ke belakang, apa yang jadi soal di atas berakar pada sejarah
kebijakan pembangunan Aceh. Aceh saat itu berada dimasa kepemimpinan
Gubernur Prof. Dr. Ibrahim Hasan (1983–1993). Di bawah instruksi langsung
Presiden Soeharto, Aceh diarahkan untuk mengembangkan sektor perkebunan
kelapa sawit sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional berbasis
agribisnis. Kebijakan yang dikemudian hari tidak berlebihan apabila disebut
hanya menempatkan kawasan ini sebagai komoditas ekonomi semata.
Melihat peluang besar untuk menarik investasi dan meningkatkan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), Aceh Singkil lantas ditetapkan sebagai
sebagai salah satu episentrum pengembangan sawit. Namun, semangat
pembangunan yang digaungkan kala itu tidak disertai dengan tata kelola yang
berkeadilan dan berkelanjutan. Alih-alih memperkuat struktur ekonomi lokal
dan memperhatikan kearifan ekologi, pendekatan top-down pembangunan
di masa Orde Baru justru mengabaikan struktur sosial dan sejarah lokal
Singkil.
Penting untuk diketahui, Singkil bukanlah wilayah yang dibangun atas dasar
keagamaan, sebagaimana wilayah Aceh pada umumnya. Sejarah kebudayaan dari
berbagai literatur masa kolonial Hindia-Belanda menunjukkan bahwa identitas
masyarakat Singkil terbentuk dari kombinasi antara struktur material yang
berbasis pada kekuatan distribusi ekonomi skala kecil-menengah lokal.
Misalnya seperti perdagangan hasil hutan, rempah, karet, kopi, hingga
produksi garam rumah tangga di wilayah bagian pesisir Singkil. Melalui
distribusi ekonomi lokal ini, kesadaran sebagai orang Singkil lahir. Ini
yang menjadi pembeda dari orang Batak, Barus, Aceh, dan Pakpak.
Singkil, sejak abad ke-7 hingga masa kolonial Hindia-Belanda, telah
menunjukkan posisinya sebagai simpul dagang strategis di pantai barat
Sumatera. Jalur sungai dan laut memungkinkan hasil bumi lokal dijual dan
ditukar dengan komoditas lain membentuk kesadaran kolektif orang Singkil
sebagai masyarakat dagang yang mandiri.
Baca Juga :
Pentingnya Penyelamatan Hutan
Hingga pada masa sekitar abad ke-16, Kerajaan Aceh memperluas dan
menancapkan kekuasaan dengan menaklukan beberapa daerah yang dekat dengan
wilayahnya, termasuk Aceh Singkil, hingga kemudian menunjuk raja kecil yang
menjadi bagian dari Kerajaan Aceh untuk mempermudah monopoli
perdagangan.
Oleh karena itu, relasi Aceh Singkil dengan Aceh terjalin dari sejarah
penaklukan militer dan penyebaran Islam oleh Kesultanan Aceh pada abad
ke-16. Dimana ini hanya menyentuh aspek simbolik dan hegemoni administratif
semata, tanpa membongkar akar sosio-ekonomi Singkil sebagai entitas yang
unik. Hal serupa juga terjadi pada suku Gayo, atau yang biasa disebut ‘suke
lee reutoeh’. Suku ini di-islamisasi dan kemudian bergabung dalam Kerajaan
Aceh.
Sayangnya, narasi pembangunan nasional tidak pernah mengakui keunikan ini.
Masuknya korporasi besar dalam sektor kelapa sawit dengan dalih
“pembangunan” telah mengubah wajah Singkil secara radikal. Hutan-hutan yang
dulunya menjadi sumber kehidupan masyarakat kini digantikan oleh hamparan
monokultur sawit. Ketiadaan pengawasan ketat dari negara, serta relasi kuasa
yang timpang antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, semakin
memperburuk situasi.
Fakta bahwa banyak perusahaan sawit yang tidak menjalankan kewajiban plasma
dan tetap beroperasi meski izin HGU-nya habis, serta mencemari
lingkungan—seperti kasus PT Ensem Lestari dan PT Socfindo—menunjukkan betapa
kuatnya pengaruh modal terhadap kebijakan negara.
Pembangunan yang hanya berlandaskan pada keuntungan ekonomi jangka pendek
tanpa mempertimbangkan warisan sejarah, ekologi, dan struktur sosial
masyarakat lokal, hanya akan menciptakan konflik berkepanjangan.
Singkil, yang sejatinya memiliki karakter historis sebagai masyarakat
dagang dengan memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan, kini
terperangkap dalam skema pembangunan yang eksploitatif dan mencabut
akar-akar sejarahnya sendiri. Maka, sudah saatnya kita menggugat ulang
paradigma pembangunan yang diterapkan selama ini. Mengembalikan narasi
pembangunan kepada masyarakat lokal, bukan kepada kepentingan modal
semata.
Baca Juga :
Mangrove Dan Manusia Dalam Kacamata Antropologi Ekologi
Kita menaruh harapan besar, sekaligus memberikan dukungan penuh kepada
gerakan yang tumbuh dari akar rumput, baik yang dilakukan oleh masyarakat
adat, mahasiswa, komunitas lokal, maupun individu-individu yang peduli akan
keberlangsungan wilayah Aceh Singkil. Bukan sekadar bentuk perlawanan
terhadap dominasi modal dan kuasa perusahaan, tetapi juga sebuah ikhtiar
kolektif untuk merebut kembali hak-hak ekologis, sosial, dan historis
masyarakat Singkil yang selama ini terpinggirkan.
Sudah terlalu lama perusahaan-perusahaan besar leluasa bergerak dalam
lingkar inti pemerintahan Aceh Singkil. Mereka menyusup ke dalam celah-celah
kekuasaan, dan menggerus tanah serta hutan yang menjadi saksi panjang dan
luasnya mozaik sejarah Aceh Singkil.
Kini saatnya gerakan rakyat menguat sebagai daya penyeimbang, dan bahkan
pengarah kebijakan publik yang berpihak kepada keberlanjutan lingkungan dan
identitas lokal. Hutan, sungai, dan tanah bukanlah sekadar objek ekonomi,
melainkan bagian integral dari warisan budaya dan sejarah Aceh Singkil yang
harus dijaga untuk generasi mendatang.
Perjuangan ini bukan hanya tentang menolak eksploitasi, tetapi tentang menegaskan kembali siapa kita sebagai orang Singkil, masyarakat yang hidup dari dan untuk tanahnya sendiri. Masyarakat yang memiliki sejarah panjang, kesadaran lokal, dan keberanian untuk mempertahankan ruang hidupnya. [*]














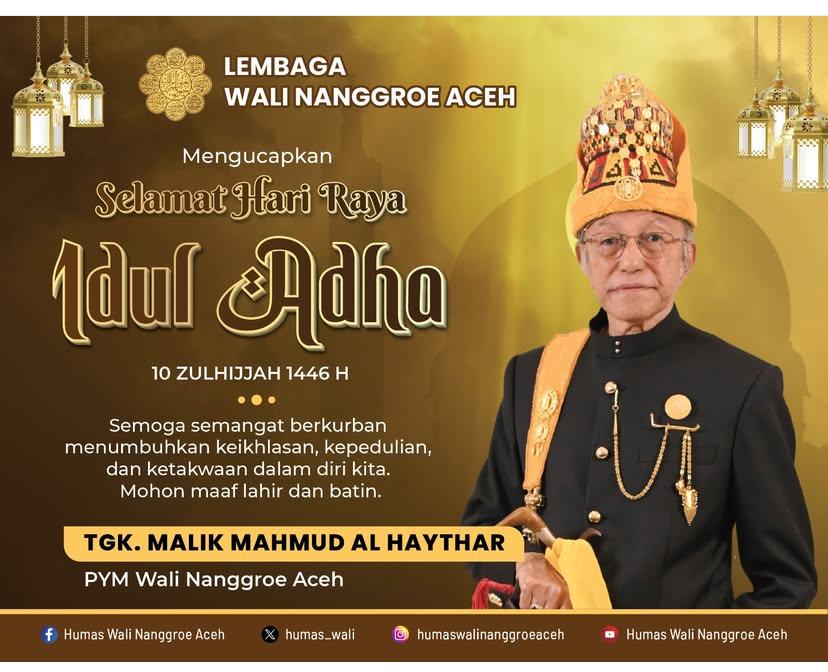
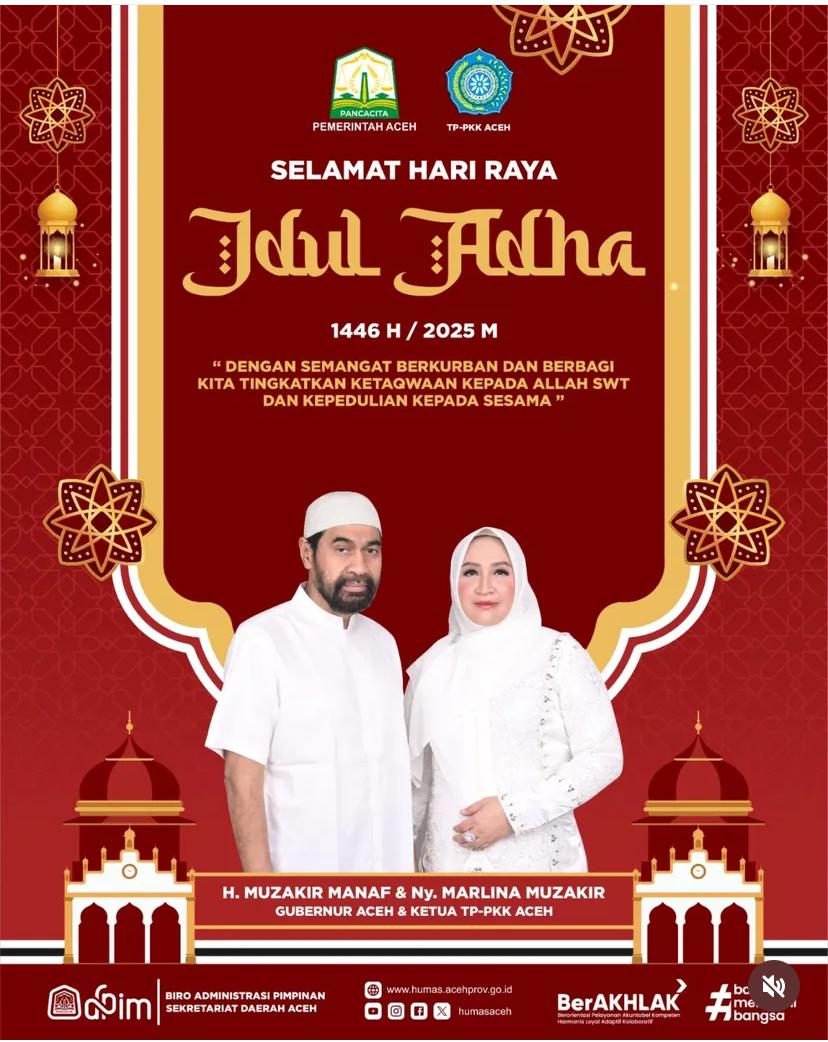








Tidak ada komentar